OLEH: Desmaiyanti[1]
“Apakah saudara siap untuk tidak pulang meskipun orang tua saudara
meninggal dunia”. Itulah pertanyaan mengerikan dalam wawancara program SM3T
yang selalu terngiang-ngiang di telingaku. Saat itu aku menjawab dengan suara
bergetar, “ya, saya siap, karena saya yakin mereka menginginkan saya melunasi
janji pengabdian saya di negeri orang”. Dalam hati saya berdoa semoga tidak ada
kisah duka di tengah pengabdian ini. Bayangkan betapa menyedihkannya tak bisa
lagi melihat wajah ibu atau ayah saat terakhir kalinya. Dan hanya bisa melihat
gundukan tanah tempat beristirahatnya.
Sesampai di rumah, aku menceritakan semua pertanyaan pewawancara. Ya,
semua. Bahkan pertanyaan yang mengerikan itu. Sempat kutatap wajah ayahku,
tenang, setenang desaku saat pagi menjelang. Tak ada sepatah katapun komentar
darinya. Satu hal yang aku tahu. Tidak ada yang akan meninggal. Ayah dan ibuku
akan baik-baik saja di sini di rumah ini. Dalam pikiranku ayah dan ibuku akan
hidup selamanya. Dan bila aku boleh memilih biarlah aku yang lebih dahulu
meninggalkan dunia ini. Karena bagiku lebih baik aku yang meninggalkan daripada
ditinggalkan. Dan aku yakin aku tak akan sanggup menahan duka itu.Jauh sebelum aku mendaftar menjadi salah satu peserta SM3T, aku telah
memberitahu keluargaku terutama ayah dan ibuku bahwa aku akan mengabdi setahun
lamanya dan tidak akan pulang sebelum masa pengabdian habis. Awalnya ibuku
menentang dan memintaku memikirkan kembali keputusanku. “Bukankah di sini kau juga
bisa mengabdi, kenapa harus pergi jauh-jauh dan tidak pulang?”. Aku berusaha
meluluhkan hati ibuku. Dan saat itu aku mendapat dukungan penuh dari ayahku.
Berdua dengan ayahku, kami berusaha menjelaskan dan membuat ibuku menyetujui
niatku. Akhirnya, dengan berat hati ibu mengijinkanku mengikuti program ini.
Dengan ridho ibu dan ayah, akhirnya aku lulus semua tes yang diadakan oleh
LPTK UNP. Dan resmilah aku menjadi guru SM3T angkatan keempat. Semenjak awal
aku menginginkan daerah penempatan di wilayah timur Indonesia. Semua cerita dan
kisah para senior sangat menginspirasiku. Tak jarang aku meneteskan air mata
hanya dengan membaca kisah manis mereka bersama mutiara hitam di sana.
Akhirnya, aku memilih Maluku Barat Daya sebagai tempat tujuanku. Tak dipungkiri,
ibuku sedikit jengkel. “Kenapa tak memilih Aceh saja agar lebih dekat dan bisa
pulang”. Aku melihat ayahku, tatapanku mengisyaratkan tanya. Ayahku hanya
tersenyum dan menjawab “pergilah, kemanapun kau ingin melangkah, tak mengapa
asalkan masih di Indonesia”. Jantungku berdegup kencang dan air mata
menggenang. Lelaki pendiam itu selalu membesarkan hatiku. Lihatlah tak sepatah
katapun dia melarangku. Ibuku memang sering berbeda pendapat dengan ayah,
tetapi kalau ayah sudah berkata begitu ibu pun tak akan lagi menentang.
Sebenarnya ibu sangat mematuhi apa yang dikatakan ayah meski kadang di awal
terlihat menentang.
Hari itupun tiba, sehari sebelum berangkat ke daerah penempatan aku sempat
pulang ke rumah. Ayahku telah menyiapkan koper yang akan kubawa. Tak lupa
dengan tali pramuka untuk mengikat koper agar tidak koyak. Ibu juga sudah
menjahitkan dua buah kain sarung untuk selimutku. Aku yang sibuk menyiapkan
keperluanku tak sempat lagi walau hanya untuk duduk dan mendengarkan nasehat
ayah dan ibu. Aku terlelap kelelahan karena memang beberapa hari ini tenagaku
disita saat prakondisi. Aku tahu malam itu ibuku tak henti-hentinya
memandangiku yang sedang tidur. Gamang anak gadisnya akan merantau sejauh itu.
Esok paginya, ibu dan ayahku hanya bisa melihatku mondar-mandir bersiap untuk
berangkat ke bandara. Kucium tangan ibuku, kupeluk erat, lama sekali. Kusimpan
aroma tubuh dan senyumannya di batok kepalaku. Begitu juga ayahku. Tangannya
yang kurus kering, dimana-mana pembuluh darahnya menyembul. Begitu banyak bekas
luka di tangan itu. Ayahku hanya tersenyum. Dan dari begitu banyak nasehat yang
ingin kudengar darinya, hanya sepatah kata yang keluar “hati-hati di negeri
orang, jaga kesehatan”. Ya, hanya itu. Tak lebih. Saat itu tidak ada rasa
khawatir dalam hatiku. Aku yakin setahun hanya sebentar. Dan saat aku kembali,
aku akan bertemu lagi dengan lelaki pendiam itu.
Ayah dan ibu sempat mengantarkanku menaiki mobil angkutan pedesaan yang
biasa mengantarkan penumpang ke Bukittinggi. Ayah dan ibu tidak mengantarkanku
ke bandara. Meskipun begitu inginnya aku diantarkan seperti teman-teman yang
lain tetapi aku tidak mau menyusahkan ibu dan ayahku karena perjalanan yang
lumayan jauh. Lama kutatap wajah ayah dan ibu dari dalam mobil pun juga mereka,
tak lepas mata mereka memandang. Ayah memandangku sendu, tetap dengan senyuman
sambil sesekali menghisap rokok. Lelaki itu ringkuh. Begitu kurus. Batuk karena
rokok sesekali keluar dari mulutnya. Aku tidak pernah khawatir dengan batuk
itu. Yang kutahu ayahku tidak pernah sakit. Ayahku seorang lelaki yang kuat.
Kekuatannya itulah yang sekarang menular padaku. Tak pernah terlintas dalam
pikiranku kalau itu adalah pertemuan yang akan sangat kuridukan.
Sesampai di bandara, akupun bertemu dengan teman-teman sepenempatan. Mereka
diantar rombongan keluarga. Tangispun sesekali pecah dan kulihat wajah-wajah
yang tidak rela melepas anak, adik, atau kakak mereka merantau begitu jauh. Aku
sempat heran, kenapa begitu banyak tangis. Bukankah setahun itu hanya
senbentar. Hanya itu yang ada dalam otakku. Semangatku ingin segera bertemu
siswa-siswa dan keluarga baru membutakan mataku. Semangatku terlalu
menggebu-gebu. Membuatku lupa kalau aku akan merasakan sakitnya merindu. Karena
selama ini aku tidak pernah merasakannya.
Setelah mengetahui bahwa di tempatku nanti tidak akan ada sinyal, barulah
aku panik. Kenyataan bahwa aku harus melakukan perjalanan laut satu hari satu
malam untuk mendapatkan sinyal mulai membuatku khawatir. Awalnya aku pikir,
mungkin memang sulit sinyal tetapi paling-paling aku harus memanjat pohon atau
mendaki bukit agar bisa mendapatkan sinyal. Itu akan sangat menyenangkan. Tapi
lihatlah, kapal yang baru akan datang sebulan sekali membuatku gundah. Belum
lagi kondisi laut yang tak menentu kadang membuat kapal batal berlayar.
Bagaimana aku akan berkomunikasi dengan ayah dan ibuku.
Sebulan berada di daerah penempatan, bertemu dengan siswa-siswa yang sangat
menyenangkan sedikit mengobati rinduku dengan rumah. Budi bahasa, sopan santun,
serta senyum yang selalu menyapaku setiap hari membuatku bersemangat. Tatapan
mata dan semangat ingin tahu mereka sedikit mengalihkan pikiranku. Setiap hari
mereka menghiburku dan mengajakku berpetualang. Menikmati semilirnya angin laut
dan deburan ombak. Memasuki hutan untuk sekedar memetik buah jambu monyet dan
mengumpulkan kacang mete. Atau mengajakku mencuci di aliran sungai yang jernih.
Mendengarkan cerita horor dan tertawa terkekeh-kekeh mendengarkan kisah lucu
dan pantun jenaka mereka. Bukan hanya siswa, mama-mama pun tak jarang mengajakku
berkeliling kampung untuk sekedar melihat pertandingan voli yang sangat
digemari semua warga. Bahkan bapak-bapak pun sering mengajakku untuk memancing
di tengah laut meskipun tak seekor ikanpun aku dapatkan. Tertawa bersama dengan
bocah-bocah saat mandi bersama di tepi pantai. Kebersamaan dan kasih sayang
mereka yang sederhana membuatku tidak terlalu memikirkan masalah sinyal lagi.
Tapi empat bulan berlalu hatiku mulai tak tenang. Entah mengapa pertanyaan
saat wawancara kembali terngiang-ngiang di kepalaku. Sudah dua kali aku ke
Kupang, kota yang menyediakan sinyal, untuk menelepon. Dan tak sekalipun aku
sempat berbincang dengan ayahku. Setiap aku bertanya dimana ayah, ibu selalu
bilang ayah ada di ladang atau tidak ada di rumah. Dongkol dan kesal. “Hei ayah,
tidakkah kau sedikit rindu dan khawatir padaku?”. Aku tahu ada yang tidak
beres. Akhirnya aku memutuskan menghabiskan liburan semester 1 di Ambon agar
aku bisa tahu apa yang terjadi.
Lima hari aku berada di Ambon, tapi kondisinya tetap sama. Aku tetap tidak
tahu apa yang terjadi. Perjalanan laut yang memakan waktu lima hari dari pulau
penempatanku membuatku hanya bisa menikmati sinyal sebentar saja. Terbatasnya
kapal yang menuju pulauku membuatku memutuskan untuk menyambung perjalanan
dengan kapal berbeda dan singgah dahulu di pulau Moa, tempat kota kabupaten
berada. Untunglah, di sini ada sinyal. Jadi, aku masih bisa berkomunikasi
dengan keluargaku. Kebetulan di sana juga ada temanku sesama SM3T sehingga aku
tidak perlu khawatir dimana akan menginap.
Takdir itu terkadang aneh dan membingungkan. Niatku agar cepat kembali ke
pulauku ternyata tidak bisa terlaksana. Kondisi laut yang sedang tidak bagus
membuat kapal-kapal tertahan dan tidak diizinkan berlayar. Rasa cemas karena
meniggalkan siswa terlalu lama membuatku bertanya-tanya apa akhir kisahku ini.
Mungkin hanya ombak dan semilirnya angin yang tahu bahwa Tuhan sangat
menyayangiku dibalik kisahku.
Malam itu, kami mendengar kabar salah satu warga Toun, tempat aku menginap,
meninggal dunia karena beberapa hari lalu menjadi korban kebakaran di rumahnya.
Tak ambil tempo, kamipun melayat. Ternyata seorang kakek-kakek. Postur tubuh
yang ringkih dan kurus itu mengingatkanku pada ayahku. Tiba-tiba air mataku
mengalir. Tangisku tak bisa kutahankan. Ada rasa takut dalam hatiku. Dalam hati
aku berdoa semoga ayahku baik-baik saja.
Akhirnya malam itu aku mengetahui apa yang terjadi. Beberapa saat setelah
kembali dari melayat, kakak tertuaku meneleponku. Dia mengatakan bahwa ayahku
dibawa ke rumah sakit, hanya dinfus karena susah menelan makanan. Memang sudah
beberapa bulan ini ayah susah berbicara dan menelan karena ada tumor yang
sedang menggerogoti tenggorokannya. Itulah mengapa ayah tidak pernah menelepon.
Kalaupun dia ingin menelepon, tidak ada suara yang keluar. Jantungku berdegup
kencang dan air mataku mengalir. Oh, ayah betapa malang nasibmu. Terbayang
olehku badannya yg semakin kurus terbaring di tempat tidur.
Keesokan harinya, kakakku yang kedua juga meneleponku. Da memintaku
berbicara dengan ayah. Meskipun tak ada suara yang terdengar di ujung telepon,
aku tetap berbicara. “ayah jangan lupa minum obat, ayah jangan sakit, ayah yang
rajin makannya biar cepat pulang, biar saat ides pulang nanti ayah sudah ada di
rumah”. Kusembunyikan isakku. Perih teriris-iris rasanya hatiku. Ingin rasanya
aku pulang dan memeluknya. Tak tega harus melihat ayahku merasakan sakit.
Masih teringat jelas dalam benakku. Sore itu, tanggal 21 Januari 2015 dan
bayangkan baru semalam aku meneleponnya. Tepat jam lima sore, hpku berbunyi. Dengan
cepat kulihat, disana tertulis my family da ya. Jantungku berdegup kencang,
hatiku was-was. Aku masih ingat kakakku tidak langsung mengatakan apa-apa. Dia
bertanya apa aku sudah makan atau belum, di sana ada temanku atau tidak. Aku
sudah mulai curiga. Setelah tahu aku sudah makan dan tidak sendiri dengan pelan
dia berkata “ayah sudah tenang, ayah sudah tidak sakit lagi”. Sontak aku
berteriak meminta penjelasan, mataku panas dan tak terasa air bening sudah
mengalir di pipiku. Aku tahu dan aku mengerti apa maksudnya. Tapi aku tidak mau
tahu dan tidak mau mengerti. Hanya isak tangis yang keluar dari mulutku.
Kakakku yang tidak tahan mendengarku menangis langsung menutup telepon. Oh
Tuhan, ternyata ini ujung kisahku. Baru beberapa hari aku bertanya-tanya kenapa
begitu lama datangnya kapal. Ternyata Tuhan memberikanku kesempatan mengetahui
berita duka ini. Seandainya saja aku telah sampai di pulau penempatanku yang
tidak ada sinyal mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa ayahku telah tiada.
Mungkin aku hanya akan mengetahuinya nanti saat sampai di rumah.
Lemah rasanya semua persendian. Ada banyak tanya dalam kepalaku. Mengapa?
Mengapa sekarang saat aku sendiri dan tidak ada keluarga? Mengapa harus ayahku?
Mengapa ayahku tak pernah melarangku pergi jika dia tahu waktunya bersamaku
takkan lama lagi? Mengapa semua ini terjadi padaku? Dan lihatlah sekarang,
betapa malangnya diriku. Aku tidak akan pernah bisa melihat ayahku meski untuk
yang terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah bisa menjalankan kewajiban terakhirku
sebagai seorang anak. dan lihatlah, pertanyaan mengerikan itu akhirnya
benar-benar datang padaku. Pantas saja, suaraku bergetar dan mataku panas saat
menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang awalnya tak pernah benar-benar
kupikirkan karena begitu besarnya semangatku ingin mengabdi. Dan memang aku
sadar, bukan larangan yang membuatku tidak bisa melihat wajah ayahku untuk yang
terakhir kalinya tetapi alam lah yang membatasiku. Terkadang aku benci pada
lautan yang membuatku tidak bisa pulang.
Saat aku pulang, bayanganku selama ini jadi kenyataan. Aku hanya bisa
melihat gundukan tanah yang sudah mengering. Tanah itu tidak lagi merah.
Inginku puaskan tangisku. Aku teringat dulu saat aku kecil, ketika aku menangis
ayahku akan marah dan berkata “apa yang kau tangiskan, apakah ayahmu meninggal
sampai kau menangis seperti itu?”. Oh ayah, bolehkah aku menangis sekarang?
Satu hal yang membesarkan hatiku. Ayah yang meminta keluargaku merahasiakan
sakitnya. Dia ingin aku tidak khawatir dan tetap fokus menjalankan pengabdian.
Dan bahkan di ujung rasa sakitnya tak pernah sekalipun dia memintaku untuk
pulang. Dia bangga melihat anaknya bisa mengabdi dan membantu pendidikan di
negeri ini. Dan sampai akhirpun, ayah tetap ingin aku melunasi janjiku untuk
mengabdi. Meskipun aku takkan pernah lagi bisa melihat wajahmu ayah, izinkan
aku membuatmu bangga dan meringankan bebanmu di sana. Jika orang bilang
pengabdian butuh pengorbanan maka itu benar. Dan lihatlah betapa besar yang
harus kukorbankan. Semoga semua perjuangan ini tetap berlanjut dan pengorbanan
ini tidak menjadi sia-sia.
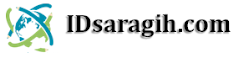











Terima kasih atas kunjungannya di blog "IDsaragih.com". Pertanyaan dan komentar silahkan tuliskan pada kotak komentar dibawah ini.
EmoticonEmoticon